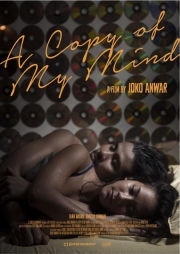oleh: wanulk
oleh: wanulk
Sekarang ini adalah era yang sangat menyenangkan bagi comic-book enthusiast di seantero jagad. Bagaimana tidak? Dalam hampir dua dekade ke belakang, entah sudah berapa banyak film-film adaptasi dari komik yang muncul ke permukaan. Tidak semua memuaskan memang. Tapi beberapa sanggup melewati ekspektasi dan bisa diterima, tidak hanya di kalangan pecinta komik, juga kalangan penonton kasual.
Pada tahun 2016 ini, Batman v Superman: Dawn of Justice keluar sebagai kick-start project dari DC Entertainment –yang sudah ketinggalan kereta jauh dari Marvel— untuk memulai cinematic universe-nya sendiri. BvS yang disutradarai oleh Zack Snyder (300, Watchmen, Man of Steel) ini bukanlah sekedar film, tapi juga merupakan event besar bagi pecinta film superhero, sebab di sinilah akhirnya dipertemukan dua ikon pop terbesar dari komik superhero; Batman dan Superman. Tentu saja ini menimbulkan hype dan antusiasme yang tinggi. Personally, I wanted this film to be good, because, at heart, I’m a big fan of both Batman & Superman. Lantas, apakah BvS dapat menjawab segala ekspektasi besar yang tersemat di pundak kekar kedua tokoh ini? (halah)
Akhirnya semuanya terjadi juga. BvS dimulai dengan narasi Bruce Wayne (Ben Affleck), disertai dengan montage trauma masa kecilnya –yang sudah sering kita lihat berulang kali di film-film Batman sebelum ini– dan juga adegan klimaks dari Man of Steel; pertarungan antara Superman (Henry Cavill) dan General Zod (Michael Shannon). Adegan awal ini mungkin dimaksudkan untuk setting keseluruhan tone dari filmnya. Namun pada perjalanannya, ternyata terjadi inkonsistensi, dengan adegan-adegan yang ada terasa seperti tambal sulam saja. Struktur penceritaannya tidak teratur dan malah menjadi cenderung berantakan, sehingga paruh awal BvS terlihat tidak fokus, membingungkan, dan bertele-tele.
Duet penulis Chris Terrio – David S. Goyer seolah kesulitan untuk meramu plotnya secara tepat. Dengan aim yang sangat ambisius untuk memulai expanded universe dari DC cinema, membuat kesemua yang ingin diceritakan terlihat bertumpuk dan pada akhirnya terasa sesak sekali. Treatment dari Snyder pun tidak banyak membantu dalam penuturan serta penerjemahan ceritanya ke layar. Ada banyak yang ingin diceritakan, ada banyak yang ingin dituturkan, tapi dengan durasi ‘hanya’ 150 menit tidaklah cukup untuk membangun sesuatu yang telah dibangun oleh rival, Marvel, bahkan dalam beberapa film. Inilah yang membuat karakter-karakter utama dalam filmnya sendiri tidak mempunyai ruang yang cukup untuk bernafas dan berkembang dengan baik untuk mengakrabkan diri dengan penonton.
Belum lagi soal intrik dan konflik yang ada. Semua terasa kentang dan tidak tereksplor dengan baik, akibat dari struktur yang tidak jelas tadi. Isu-isu yang sebelumnya sudah came up malah terlewat begitu saja. Hal ini mengakibatkan motivasi karakternya pun menjadi kabur dan pada akhirnya konflik pun dimunculkan dengan penyebab yang terasa sangat artifisal serta konyol. Lah, penulis skenarionya saja terlihat tidak terlalu yakin dengan penyebab kenapa Batman dan Superman bisa jadi berseteru, bagaimana untuk meyakinkan penonton?
Di luar semua komplain saya di atas, sebetulnya masih ada hal-hal baik yang bisa sedikit memaafkan itu semua. Paruh kedua film ini sebenarnya terasa lebih baik dari paruh awal yang terasa draggy dan confusing. Adegan klimaksnya (well, both of them) pun disajikan dengan cukup baik dengan visual signature khas Zack Snyder.
Satu yang paling saya sukai adalah pembawaan dari masing-masing aktor dan aktris untuk masing-masing karakternya. Cavill semakin matang baik sebagai Supes atau Clark Kent. Beberapa momen dramatis (terutama percakapan antara Clark dan Martha Kent di teras rumah) dapat bekerja dengan baik di layar lewat akting solid darinya. Ben Affleck, yang sebelum ini sangat diragukan dan casting-nya dianggap kontroversial untuk seorang Bruce Wayne/Batman, malah mengalahkan semua ekspektasi buruk terhadapnya. Dia berhasil membawakan Bruce Wayne tua yang rapuh dan penuh amarah, juga pembawaannya sebagai Batman bisa dibilang cukup baik (walau ada satu detail dalam versi Batffleck yang saya kurang suka, tapi itu mungkin lebih ke kesalahan Snyder). Dan yang paling keren tentu saja Gal Gadot sebagai Diana Prince yang menjadi scene stealer di setiap adegan dimana dia berada. Scene presence-nya sebagai Wonder Woman sangat luar biasa mewah and it WILL give you the chills. Even Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor ‘alternatif’pun tidak terlalu buruk menurut saya. Paling tidak, menurut saya tidak se-annoying yang beberapa orang tuduhkan. Oh, and you gotta love Jeremy Irons’ Alfred. He’s like the coolest Alfred on screen.
Selain itu, BvS masih bisa menyuguhkan beberapa nod cukup bagus ke beberapa source material dan cerita komik ikonik dari kedua karakter utama film ini (mulai dari The Dark Knight Returns dan The D**** of Superman). Yah, walaupun beberapa ada berasa keluar konteks dan ‘dimasuk-masukin aje’, tapi bisa juga memunculkan beberapa geeky moment yang cukup exciting.
All in all, Batman v Superman: Dawn of Justice mungkin bukanlah merupakan sebuah home run dari upaya DC ini memulai cinematic universe-nya. Toh, paling tidak, dengan perolehan Box Office yang masih mentereng, kepastian sekuel masih tetap terjaga. Nah, disitulah DC mesti berupaya menemukan cara untuk memperbaiki kesemuanya agar cinematic universe-nya bisa bernafas panjang. Either way, it’s still a very watchable flick with enough excitement. Tak usah terlalu dengar beberapa review keras dari kritikus (termasuk yang abal-abal macam saya, hahaha). Tonton saja, nikmati pengalamannya, dan nilai sendiri filmnya. Ciao.

Producers: Charles Roven & Deborah Snyder Writers: Chris Terrio & David S. Goyer Music: Hans Zimmer & Junkie XL Cinematographer: Larry Fong Editor: David Brenner Director: Zack Snyder Cast: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Diana Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter, Scott McNairy
Score: B-
 oleh: wanulk
oleh: wanulk